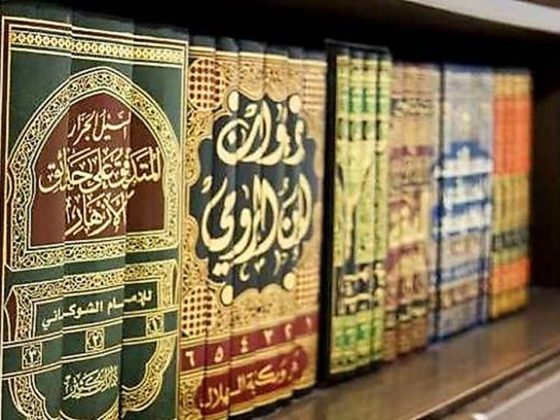Wasathiyah berasal dari akar kata “wasatha”. Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Mashry, pengertian wasathiyah secara etimologi berarti:
وَسَطُ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرْفَيْهِ
Artinya: “sesuatu yang berada (di tengah) di antara dua sisi”
Dalam khazanah Islam klasik, pengertian wasathiyah terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuḥaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya.
Menurut Ibnu ‘Asyur, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.
Menurut al-Asfahany, kata wasathan berarti tengah-tengah di antara dua batas (a’un) atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan ekstrem (tafrith).
Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ, kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan di antara dua ujung.
“Dan demikianlah Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan”, artinya “dan “demikianlah Kami memberi hidayah kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Kami memindahkan kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as dan Kami memilihkannya untuk kalian.
Kami menjadikan Muslimin sebagai pilihan yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan dalam setiap hal, tidak ifrath dan tafrith dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (ghuluw) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya.”
Al-Thabary memiliki kecenderungan yang sangat unik, yakni dalam memberikan makna seringkali berdasarkan riwayat. Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasath bermakna al-‘adl, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.
Di antara redaksi riwayat yang dimaksud, yaitu:
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَال: عُدُوْلًا .
Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan”. Beliau berkata: (maknanya itu) adil.”
Berdasarkan pengertian tersebut, seringkali dipersoalkan mengapa Allah lebih memilih menggunakan kata al-wasath dari pada kata “al-khiyar”? Jawaban terkait hal ini setidaknya ada dua sebab, yaitu:
Pertama, Allah menggunakan kata al-wasath karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain. Sedangkan posisi saksi semestinya harus berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (proporsional). Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik.
Kedua, penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.
Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (tafrith), terpilih, adil dan seimbang.
Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata “wasathan” yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (al-tawazun), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (ruhiyah) dengan material (madiyah). Individualitas (fardiyyah) dengan kolektivitas (jama’iyyah).
Kontekstual (waqi’iyyah) dengan tekstual. Konsisten (tsabat) dengan perubahan (taghayyur). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (universum), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi.
Bahkan, amal menurut Islam bernilai shaleh apabila amal tersebut diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris (hablun minallah) dan anthropocentris (hablun min al-nas).
Menurut Din Syamsuddin, terdapat pula interpretasi wasathiyah sebagai al-Shirath al-Mustaqim. Konsep jalan tengah tersebut, tentu tidak sama dengan konsep the middle way atau the middle path di bidang ekonomi konvensional.
Wasathiyah dalam Islam bertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia.
Hal ini membawa pada pemahaman tentang adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan (al-‘Alaqah bain al-Khaliq wa al-Makhluq), sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos (al-Qiyas bain al-‘Alam al-Kabir wa al-’Alam al-Shaghir) menuju satu spot, titik tengah (median position).
Menurut Hasyim Muzadi:
الْوَسَطِيَّةُ هِيَ اَلتَّوَازُنُ بَيْنَ الْعَقِيْدَةِ وَالتَّسَامُحِ
Artinya: “Wasathiyah adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi”.
Syarat untuk merealisasikan sikap wasathiyah yang baik tentu memerlukan akidah dan toleransi, sedangkan untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang wasathiyah.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan wasathiyah dapat dipadukan bahwa; keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.
Keseimbangan tersebut bisa terlihat dengan kemampuan mensinergikan antara dimensi spiritualitas dengan material, individualitas dengan kolektivitas, tekstual dengan kontekstual, konsistensi dengan perubahan dan meletakkan amal di dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara theocentris dan anthropocentris, adanya korespondensi antara Pencipta dan ciptaan sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos menuju satu spot yaitu median position. Keseimbangan yang mengantarkan pada al-Shirath al-Mustaqim tersebut yang nantinya akan melahirkan umat yang adil, berilmu, terpilih, memiliki kesempurnaan agama, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang lembut dan beramal shaleh.
Salah satu ciri dari Islam adalah wasathiyah. Kata wasathiyah memiliki beberapa makna, yakni menurut bahasa Indonesia artinya adalah moderasi. Menurut Afifuddin Muhadjir, makna wasathiyah sebetulnya lebih luas dari pada moderasi.
Wasathiyah bisa berarti realistis (Islam Wasathiyah yaitu Islam yang berada di antara realitas dan idealitas). Yakni, Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk menyejahterakan umat di dunia dan akhirat. Cita-citanya yang melangit, tapi ketika di hadapkan pada realitas, maka bersedia untuk turun ke bawah.
Wasathiyah yang disebut dalam QS: al-Baqarah 143 dapat juga diartikan jalan di antara ini dan itu. Dapat juga dikontekstualisasikan Islam Wasathiyah adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula, Islam antara jasmani dan ruhani.
Dalam kitab-kitab fiqih, seorang presiden itu harus mendalam terkait hal agama, mujtahid dan dipilih secara demokratis. Bagaimana ketika yang menjadi presiden justru kebalikannya? Apakah kita harus memberontak?
Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian. Kitab-kitab fiqih menyatakan, para hakim harus seorang mujtahid dan memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya.
Keputusan hakim adalah kepastian dan keadilan. Tapi apabila kebalikannya, yakni tidak terlaksana sebagaimana aturannya. Apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian.
Meskipun kita harus tetap mengingatkannya, tapi cara yang ditempuh harus baik.
Al-wasathiyah disebutkan dalam QS: al-Baqarah: 143 dan QS: al-Nisā’: 171.
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.
Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kalian mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara”.
خَيْر الْأُمُور أَوْسَاطهَا
Artinya: “Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan”.
Realiasasi wasathiyah dalam ajaran Islam secara garis besar dibagi tiga: akidah, akhlak dan syariat (dalam pengertian sempit). Ajaran akidah berarti terkait konsep ketuhanan dan keimanan. Akhlak berarti terkait penghiasan hati melalui sikap dan perilaku seseorang agar dapat menjadi indivisu mulia.
Sedangkan syariat dalam pengertian sempit, berarti ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (al-ahkam al-‘amaliyah).
Salah satu segmen dalam syariat adalah fiqih. Syariat dari segi sifatnya ada dua: tsabit dan mutaghayyirah. Syariat tsabit adalah syariat yang tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun, sedangkan syariat mutaghayyirah adalah syariat yang dapat berubah sehingga dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat.
Akidah, akhlak dan syariat tsabit tidak dapat dirubah. Sedangkan syariat mutaghayyirah dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Wasathiyah masuk pada akidah, akhlak, syariat tsabit dan mutaghayyirah.
Wasathiyah dalam bidang akidah, seperti posisi Islam yang berada di antara atheisme (tidak percaya Tuhan) dan politisme (kelompok yang percaya adanya banyak Tuhan). Wasathiyah dalam bidang akhlak, seperti posisi di antara khauf (pesimisme) yang berlebihan dan raja’ (optimisme) yang berlebihan.
Optimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang berbuat dosa, sehingga menganggap dirinya pasti mendapatkan surga. Di antara ayat yang menjadi landasan adalah QS: al-Baqarah: 173:
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Artinya: “Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Sedangkan pesimisme yang berlebihan dapat mengakibatkan orang gampang putus asa. Di antara landasan ayat yang sering digunakan adalah QS: al-A’raf: 99:
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
Artinya: “Apakah mereka tidak percaya ancaman Allah. Maka tidak ada yang dapat merasa aman dari ancaman Allah, kecuali orang-orang yang merugi.”
Di antara contoh orang yang pesimis adalah pembunuh Sayyidina Hamzah dengan memutilasinya. Pada saat masuk Islam, ia merasa pesimis akan kemungkinan mendapatkan ampunan Tuhan dari perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut. Kemudian turun QS: al-Zumar: 53.
قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Artinya: “Katakanlah (Muhammad), wahai hambaku, orang-orang yang sudah berlebihan atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Penyayang.”
Wasathiyah dalam bidang syariat (khususnya ekonomi) diindikasikan dalam QS: al-Furqan: 67, yakni tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
Artinya: “dan orang-orang ketika menafkahkan, mereka tidak berlebihan dan tidak pelit dan di antara keduanya adalah ketegakkan.”
Wasathiyah dalam bidang manhaj berarti menggunakan nash al-Qur’an dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari’ah). Nash-nash dan tujuan-tujuan syariatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yakni nash-nash yang dapat dijelaskan melalui tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan-tujuan syariat lahir dari nash-nash Islam.
Tjuan-tujuan syariat merupakan hasil penelitian ulama zaman dahulu, sedangkan yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan yang termaktub dalam nash-nash al-Qur’an dan hadis, berikut hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dunia dan akhirat dengan mengindahkan kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”
Maksudnya adalah apabila seseorang hendak menafsirkan nash-nash, maka harus memerhatikan tujuan-tujuan syariatnya. Tentu aturan yang lahir akan berbentuk tekstual dan kontekstual. Secara kaidah, apabila dihadapkan pada mashlahah dan mafsadah, maka yang didahulukan adalah yang mashlahah.
Tapi apabila dihadapkan pada mashlahah ghairu mahdlah (kemaslahatan tidak murni) dan mafsadah ghairu mahdlah (kerusakan tidak murni), maka pilihannya adalah yang terdapat mashlahah yang lebih besar. Tujuan-tujuan syariat melahirkan dalil-dalil primer (الأَدِلَّةُ القَطْعِيَّة) dan sekunder (الأَدِلَّةُ الفَرْعِيَّة).
Tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, sebenarnya sama seperti tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatannya. Setiap negara yang sudah mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka sudah bisa disebut sebagai negara ideal dan negara khilāfah.
Afifuddin menyetujui negara dalam bingkai khilafah yang tidak seperti konsep yang diusung HTI. Khilafah yang disetujui adalah menggunakan konsepnya al-Mawardi, dimana ia mengatakan;
الإِمَامَةُ مَوْضُوْعُةً لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فيِ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَلَوْلاَ الوُلَاةُ لَكَانَ النَّاسُ فوضى مهملين وهمجاً مضيّعين.
Artinya: “kepemimpinan/khilafah adalah melanjutkan tugas kenabian, yakni: menjaga agama dan politik dunia….”.
Setiap negara yang kondusif bagi kaum Muslimin untuk melaksanakan ajaran agamanya serta dijalankan dalam pemerintahan dengan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, maka itu sudah cukup menjadi negara khilafah.
Oleh karena itu, NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, bisa saja menjadi wadahnya khilafah. Posisi sebagai wadah, NKRI tidak ada persoalan, tapi persoalan yang terjadi saat ini lebih berada pada isinya yang belum baik. Cita-cita negara yang menjamin kenegaraan yang adil dan sejahtera, maka Pancasila sudah cocok untuk mewujudkan Islam itu sendiri.
Terdapat beberapa hal yang sering dipertanyakan terkait istilah Islam Wasathiyah ini. Adakalanya mengkritisi pada padanan derivasinya, dan ada pula yang mengkritisi substansi penggunaannya.
Terkait frasa, terdapat istilah yang identik dengan Islam Wasathiyah, yaitu Wasathiyah al-Islam yang mencerminkan sebagai ajaran yang seimbang.
Terkait substansi penggunaannya, sepintas akan menjadi suatu persoalan terkait ungkapan yang termaktub di dalam nash al-Qur’an yang sejatinya adalah Ummatan Wasathan sebagaimana diindikasikan dalam QS: al-Baqarah: 143.
Sedangkan yang justru dijadikan misi perjuangan umat Islam yang moderat adalah istilah Islam Wasathiyah?
Terkait hal ini, Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI menyatakan bahwa untuk membentuk umat yang wasathan tentu diperlukan adanya ajaran, sehingga membahas ajaran Islam Wasathiyah dalam rangka merealisasikan hal tersebut, tentu menjadi suatu keniscayaan dan keharusan.
Selain mempersoalkan perihal tersebut, penggunaan istilah Islam Wasathiyah dalam prosesnya juga tidak lepas dari suatu kritik yang menyatakan bahwa penggunaan yang benar adalah Islam Wasathy, dimana kata “Islam” disifati dengan kata Wasathy yang dilengkapi dengan ya’ Nisbah.
Cholil Nafis menyatakan bahwa, penggunaan istilah tersebut terjadi pembuangan kata muannats yang asal mulanya (taqdir) yaitu الإِسْلاَمُ عَليَ طَرِيْقَةِ الوَسَطِيَّةِ dimana artinya yaitu Islam yang mengikuti jalan wasathiyah.
Di dalam al-Qur’an, kata ummat (أُمَّة) terulang sebanyak 51 kali dan 11 kali dengan bentuk (أُمَم). Tetapi hanya satu frasa yang disandarkan pada kata “wasathan”, yaitu terdapat di dalam QS: al-Baqarah; 143.
QS: al-Baqarah: 143
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
Artinya: “Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.”
Apabila dicermati dengan teliti, kata wasathan ini terdapat di tengah-tengah ayat al-Baqarah ayat ke 143 dan ayat tersebut juga terletak di tengah-tengah Surat al-Baqarah yang seluruh ayatnya berjumlah 286 ayat. Itu artinya, ditinjau dari segi penempatannya sudah mengindikasikan makna tengah-tengah.
Sumber: Diambil dari buku Islam Wasathiyah, Tim Penulis Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, 2019