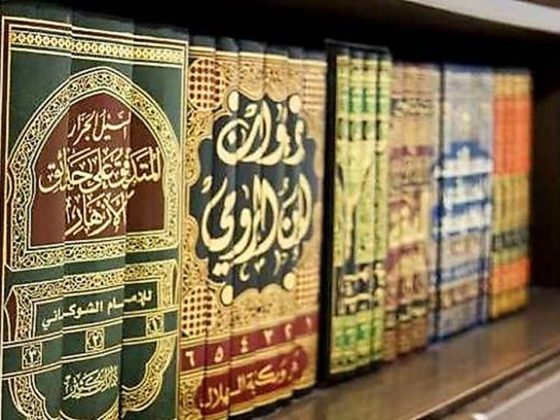(Diringkas dari Ghairul Muslimin fil Mujtama’ Al-Islami, karangan DR. Yusuf Qaradhawi)
Perlindungan terhadap harta benda
Sebagaimana perlindungan terhadap jiwa dan badan non Muslim, demikian pula perlindungan terhadap harta dan benda mereka. Hal ini merupakan kesepakatan kaum Muslimin dari semua mazhab di seluruh negeri dan pada seluruh pemerintahan yang bergantian.
Abu Yusuf meriwayatkan sebagian yang disebut dalam perjanjian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan orang-orang Nasrani Najran: “…bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan Allah dan dzimmah Muhammad, Nabi dan Rasul-Nya, atas harta-benda mereka, tempat-tempat peribadatan, serta apa saja yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik yang sedikit ataupun yang banyak…”[1]
Diantara pesan-pesan Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah ialah: “Cegahlah kaum Muslimin dari bertindak zalim terhgadap mereka (non Muslim Ahludz-Dzimah), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya.”
Siapa yang mencuri harta milik seorang Dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta akan dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa berutang kepada seorang Dzimmi haruslah melunasinya, dan jika ia dengan sengaja mengulur-ngulur waktu pembayarannya sedangkan ia mampu, maka hakim akan memenjarakannya sampai ia bersedia membayar utangnya itu.
Perhatian dan pemeliharaan Islam terhadap kesucian harta dan milik mereka mencapai kesempurnaan, sehingga ia menghormati apa saja yang mereka anggap sebagai harta sesuai dengan agama mereka, meskipun hal itu tidak dianggap sesuatu yang berharga dalam pandangan kaum Muslimin.
Misalnya khamr dan babi, dalam pandangan kaum Muslimin bukan merupakan sesuatu yang ada harganya. Karena itu barangsiapa menghilangkan (membuang, merusak, dan sebagainya), khamr atau babi milik seorang Muslim lainnya, tidaklah ia akan didenda ataupun dijatuhi hukuman apapun, bahkan ia mendapat pahala atas perbuatannya itu. Sementara itu seorang Muslim tidak diperbolehkan memiliki sesuatu dari keduanya, baik untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada orang lain.
Akan tetapi, bila khamr dan babi itu dimiliki oleh seorang non-Muslim, kedua-duanya dianggap harta berharga olehnya. Bahkan mungkin termasuk harta yang paling berharga. Maka seperti yang dinyatakan oleh fuqaha mazhab Hanafi, barangsiapa merusak sesuatu dari kedua-duanya milik seorang Dzimmi, ia diharuskan membayar ganti harganya.[2]
Perlindungan terhadap kehormatan
Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri seorang Dzimmi seperti halnya terhadap kaum Muslimin. Siapa saja tidaklah dibolehkan mencaci seorang Dzimmi ataupun menujukan tuduhan palsu terhadapnya, menjelekkannya dengan suatu kebohongan, mempergunjingkannya dengan suatu ucapan yang tidak disukainya, baik yang bersangkutan dengan dirinya sendiri, nasabnya, perilakunya, bentuk tubuhnya atau apa saja selain itu yang berhubungan dengannya.
Syihabuddin Al-Qarafi Al-Maliki, seorang ahli fiqih dan ushuluddin menulis, “Akad dzimmah mewajibkan berbagai hak untuk mereka, sebab mereka itu berada dalam lingkungan kita, penjagaan kita, dzimmah kita, dzimmah Allah, Rasul-Nya, dan agama Islam. Maka barangsiapa membuat pelanggaran atas mereka walaupun dengan satu kata busuk atau gunjingan, ia sudah menyia-nyiakan dzimmah Allah, dzimmah Rasul-Nya serta dzimmah agama Islam.” [3]
Dalam buku Ad-Durrul Mukhtar, salah satu kitab kaum Hanafi, disebutkan: “Wajib mencegah gangguan terhadap seorang Dzimmi dan haram mempergunjingkannya seperti juga terhadap seorang Muslim.” Mengenai hal ini, Al-Allamah Ibnu Abdin memberikan komentarnya: “Karena dengan adanya akad dzimmah, ia telah memiliki hak yang sama seperti yang kita miliki. Maka seperti diharamkannya pergunjingan terhadap kaum Muslimin, haram pula pergunjingan terhadap seorang Dzimmi. Bahkan sebagian ulama menganggap kezaliman terhadap seorang Dzimmi lebih besar dosanya.” [4]
(Bersambung)
Catatan Kaki:
[1] Al-Kharaj, hal. 72.
[2] Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai hal ini. Yang disebutkan di atas adalah pendapat dalam madzhab Hanafi.
[3] Al-Furuq, jilid III, hal. 14.
[4] Ad-Durrul Mukhtar dan Hasyiya Ibnu Abidin, jilid III, hal. 244-246; cetakan Istambul.