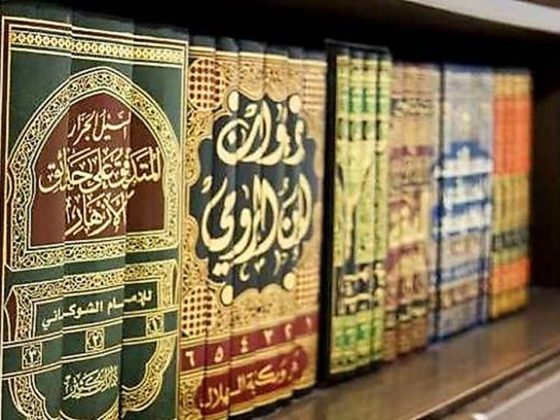Oleh: Ahmad Heryawan
Ada saat-saat yang menggembirakan pada masa kita menempuh pendidikan. Ketika kita mendapatkan nilai yang baik sehingga kita lulus dari setiap jenjang pendidikan menjadi hiasan terindah kehidupan yang kita jalani. Kenangan itu akan selalu membekas dan tidak akan hilang dalam ingatan kita. Hari wisuda indah bukan karena acara dilaksanakan di gedung mewah atau pelangi yang menghiasi cakrawala, tetapi hari tersebut menjadi indah karena kita yang menjadikannya indah dengan sikap, pikiran, dan tindakan-tindakan yang indah sehingga mendapat kelulusan terhadap sebuah jenjang pendidikan.
Secara harfiah kelulusan ini berarti berakhirnya masa pembelajaran dalam pondok pesantren, namun makna yang terkandung dalam seremoni wisuda santri merupakan langkah awal para lulusan dalam menjalani tahapan hidup bermasyarakat selanjutnya. Secara khusus bagaimana menjadi individu masyarakat dengan berkualifikasi baik dan mengamalkan ajaran Islam yang didapat selama menjadi santri, kemudian mampu mengayomi masyarakat. Individu seperti itulah yang memperjelas bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam.
Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab “fanduk” yang berarti “hotel atau asrama”. Dalam kamus bahasa Indonesia pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu”. Ada beberapa istilah yang kita temukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia terutama didaerah Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya mempergunakan istilah pesantren atau pondok, sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkung atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Kata pesantren berasal dari “santri” yang berarti orang yang mencari pengetahuan Islam, yang pada umumnya kata pesantren mengacu pada suatu tempat, di mana santri menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan.
Tertulis dalam sejarah, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i. Ibnu Taimiah mengartikan dakwah adalah mengajak untuk beriman kepada Allah dan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang mencakup ajaran Rukun Iman dan Rukun Islam. Sedangkan Abu Bakar Dzikri menjelaskan bahwa dakwah adalah bangkitnya para ulama Islam untuk mengajarkan Islam kepada umatnya, agar mereka dapat memahami agamanya, mengerti tentang makna kehidupan, sesuai kemampuan setiap ulama. Ulama secara etimologis adalah jama’ dari kata ‘alim’ yang artinya orang yang memiliki ilmu, yang membawanya takut hanya kepada Allah.
Pengertian ulama tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki kafa’ah syar’iyah (latarbelakang bidang agama) saja, tapi juga mencakup semua ahli dalam bidang keilmuan apapun yang bermanfaat, dengan syarat ilmu yang dikuasainya membawa dirinya menjadi orang yang memiliki rasa khasyyah (rasa takut) kepada Allah swt. Rasa khasyyah inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Karenanya dalam pengertian ini para kader dakwah adalah para ulama yang berperan sebagai ‘waratsatul anbiya’ (pewaris para nabi) yang selalu melakukan tawashau bil haqqi dan tawashau bis shabri (saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran).
Kita mengenal nama ulama besar seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar dan yang lainnya, melalui kepemimpinan mereka beserta para santri melakukan pemberontakan kepada penjajah. Upaya memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia di catat dengan tinta emas sejarah perjuangan Indonesia diantaranya adalah; Perang Padri di Sumatara Barat (1821-1828) yang dipelopori kaum santri di bawah pimpinan tuanku Imam Bonjol; pemberontakan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1828-1830); Pemberontakan di Aceh ( 1873-1903) yang dipimpin antara lain oleh Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro; Serta masih banyak peran ulama dan para santrinya dalam mengusir penjajah dan mengobarkan semangat nasionalisme.
Begitu juga pada era perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana diceritakan oleh Saifuddin Zuhri dalam buku Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia; KH Hasyim Asy’ari memanggil Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syamsuri dan para kiai lainnya lainnya untuk mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura atau utusan cabang NU untuk berkumpul di Surabaya. Hasilnya pada tanggal 23 Oktober 1945 Pengurus Besar NU mendeklarasikan sebuah seruan Jihad fi Sabilillah yang belakangan terkenal dengan istilah Resolusi Jihad.
Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu. Pertama, setiap muslim (tua, muda, kaya dan miskin sekalipun) wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika kita berhadapan dengan penjajah. Fatwa jihad itu kemudian digelorakan Bung Tomo lewat radio disertai dengan teriakan ‘Allahu Akbar’ sehingga berhasil membangkitkan semangat juang kalangan santri untuk melawan penjajah. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1945, dan kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari pahlawan.
Kepeloporan Ulama dan santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak selesai ketika Negara Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Pada saat Indonesia memasuki perjuangan melalui jalur diplomasi, sebagai konsekuensi perjanjian Linggarjati 1946 Indonesia berbentuk Negara Serikat. Belanda kemudian terus membuat negara-negara boneka yang pada kelanjutannya menghambat kehidupan berbangsa dalam bentuk negara kesatuan. Hal tersebut terlihat ketika aspirasi rakyat berkembang untuk mengembalikan Indonesia dengan bentuk negara kesatuan, kebanyakan negara bagian (merasa sama-sama berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) rupanya berat membubarkan diri dan melebur dengan Republik Indonesia yang mereka sebut Republik Yogyakarta.
Seorang ulama bernama Muhammad Natsir mengajukan gagasan kompromistis. Dia menyarankan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer, sehingga tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya. Tanggal 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. Pidato itu kemudian dikenal dengan “mosi integral”, yang berisi secara jelas adalah undangan bagi pemerintah agar mengambil prakarsa mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya membuat rencana mengatasi gejolak. Beliau menyarankan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer, sehingga tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya.
Begitulah para ulama terdahulu telah memberikan contoh kepada kita tentang jalan Dakwah indah dan mempraktekkan bahwa Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Tugas menyampaikan Islam kepada umat manusia seluruhnya dan mengajak mereka untuk komitmen dengan Islam pada setiap kondisi, telah mereka wariskan kepada generasi selanjutnya. Karenanya kita semua gembira dan menaruh harapan besar kepada para santri yang baru selesai masa studinya agar dapat melakukan pembaharuan masyarakat. Kehadiran individu-individu yang berilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya tersebut ditengah-tengah kehidupan masyarakat dapat menjadi agen-agen percepatan pembangunan. Diperlukan banyak ulama-ulama agen perubahan yang mampu membawa masyarakat mencapai visi pembangunannya yaitu menjadi mandiri, dinamis dan sejahtera.
(Tulisan ini adalah transkrip ceramah Ahmad Heryawan pada acara wisuda di Ponpes Refah pada tahun 2011)