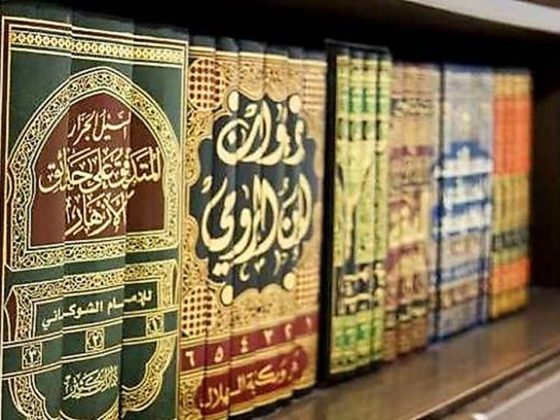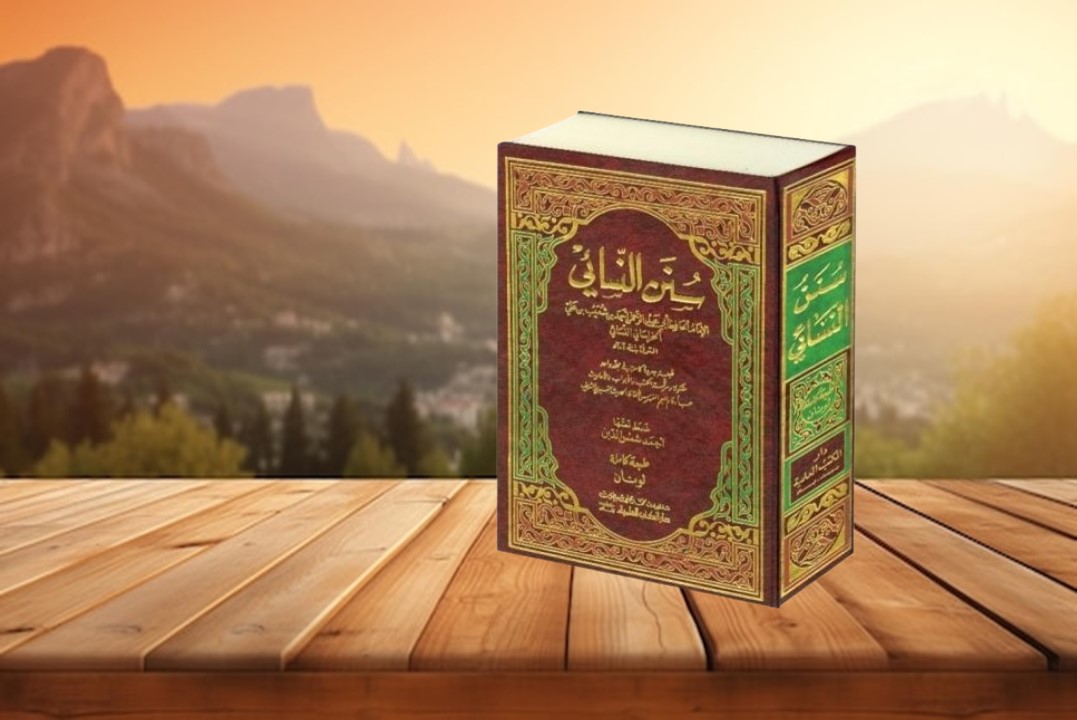Oleh: Farid Nu’man Hasan
Hadits-hadits dhaif (lemah), yang tidak bisa dipastikan asalnya dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, para ulama sepakat tidak boleh dipakai dalam perkara aqidah dan hukum agama. Ada pun penggunaan hadits dhaif untuk perkara menggalakan dan merangsang manusia untuk melaksanakan fadhailul a’mal (amal-amal utama), akhlaq, kelembutan hati, dan semisalnya, maka para ulama berbeda pendapat.
Imam An Nawawi mengklaim bahwa para ulama telah sepakat (konsensus) bolehnya menggunakan hadits-hadits dhaif untuk perkara fadhailul a’mal tersebut. Beliau mengatakan:
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
Para ulama telah sepakat bahwa bolehnya beramal dengan hadits-hadits dhaif dalam masalah fadhailul a’mal .. (Muqadimah Al Arbain An Nawawiyah)
Namun, kenyataannya hal ini termasuk khilafiyah di antara para ulama Islam. Hanya saja memang, jumhur (mayoritas) ulama membolehkan menggunakan hadits dhaif hanya untuk tema-tema fadhailul a’mal, targhib wat tarhib, dan hal-hal semisal demi mengalakan amal shalih dan kelembutan hati dan akhlak. Tetapi pembolehan ini pun mereka memberikan syarat, yakni:
- Tidak terlalu dhaif, tidak sampai perawinya tertuduh sebagai pendusta dan pemalsu hadits.
- Tidak bertentangan dengan tabiat umum agama Islam.
- Jangan menyandarkan atau memastikan dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika mengamalkannya.
Mereka yang membolehkan di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Al Hakim, Imam Yahya Al Qaththan, Imam Abdurrahman bin Al Mahdi, Imam Sufyan Ats Tsauri, Imam An Nawawi, Imam As Suyuthi, Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id, dan lainnya.
Sedangkan pihak yang menolak adalah Imam Al Bukhari, Imam Muslim, Imam Yahya bin Ma’in, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul ‘Arabi, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Nashiruddin Al Albani dan lainnya dari kalangan hambaliyah kontemporer, juga yang nampak dari pandangan Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah. Bagi mereka, selama hadits shahih masih ada, maka cukuplah bersandar dengannya, baik dalam urusan aqidah, syariah, fadhailul a’mal, akhlak, dan semisalnya. Sebab, menyibukkan diri dengan hadits dhaif, akan membuat terlupakannya hadits-hadits shahih. Menggunakan hadits dhaif, sama juga memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Tidak menggunakan hadits shahih, sama juga menghapuskan dari Islam sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian dari Islam. Inilah bahayanya.
Berikut ini saya sampaikan fatwa Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah dalam situsnya tentang menggunakan hadits dhaif untuk fadha’ilul a’mal.
Pertanyaan: Bagaimana pandangan syara’ atas para dai, penasihat, khathib, dan ulama yang banyak menyampaikan hadits-hadits dhaif, dan orang bodoh dari kalangan penuntut ilmu pemula yang tidak memahami kelemahannya, dan tidak tahu kesungguhan para ulama hadits. Jika mereka diingkari, mereka menjawab; “hadits dhaif boleh diamalkan untuk Fadhaiul A’mal, juga dalam pelajaran, dan targhib (kabar gembira) dan tarhib (ancaman).
Jawaban: (Fatwa Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah)
Bismillah, wal hamdulillah, washshalatu wassalam ‘ala rasulillah, wa ba’du:
“Sebagian ulama berpendapat bahwa dibolehkannya menyampaikan hadits-hadits dhaif dalam urusan nasihat dan bimbingan, dan dari apa-apa yang disitilahkan dengan fadhailul a’mal. Sampai-sampai banyak yang mengklaim bahwa ulama telah sepakat terhadap pendapat ini.
Tidak ragu lagi, ini adalah salah besar. Sejumlah besar para ulama muhaqqiq (peneliti) berpendapat bahwa tidak boleh mengamalkan hadits dhaif dalam fadhailul a’mal dan lainnya. Ini adalah pendapat Imam Bukhari dan dikuatkan oleh Syaikh Al Albani pada masa kita sekarang.
Lagi pula, pihak yang membolehkan mengamalkan hadits dhaif untuk Fadhail juga memberikan syarat dengan syarat yang begitu penting sampai-sampai tidak mungkin, sehingga sama saja itu sebagai hadits shahih. Syarat yang mereka keluarkan adalah: hadits tersebut kedhaifannya ringan, dan kandungannya memiliki dasar yang kuat yang telah ada pada hadits lain yang tidak dhaif, dan hendaknya si penasehat menjelaskan kepada manusia bahwa hadits tersebut adalah dhaif. Demikian.
Ulama yang luas ilmu-ilmu syariat selamanya tidak akan pernah berhujjah dengan hadits-hadits dhaif, karena hadits-hadits shahih begitu banyak dan mencukupi. Namun, orang-orang yang sering menggunakan hadits dhaif, mereka hanyalah orang-orang yang membuat mudah populernya hadits-hadits dhaif, lantaran sedikitnya pergaulan mereka terhadap hadits dan ilmu-ilmunya.”
(Dalam Fatwanya yang lain Syaikh Al Qaradhawi mengatakan):
“Banyak amal yang disandarkan oleh mereka kepada apa-apa yang telah disiarkan oleh orang yang menganggap hadits dhaif itu boleh diriwayatkan dalam fadhailul amal, kisah, targhib, tarhib, dan semisalnya.
Kami (Syaikh Al Qaradhawi) akan memberikan sejumlah peringatan sebagai berikut:
Pertama: Pendapat ini tidaklah disepakati, di sana terdapat sejumlah besar para imam mu’tabar yang menolak menggunakan hadits dhaif dalam semua bidang, sama saja baik fadhailul a’mal dan lainnya.
Itu adalah pendapat Imam Yahya bin Ma’in, dan segolongan para imam, dan juga zahirnya pendapat Imam Al Bukhari; orang yang telah meneliti dengan cermat dan detil terhada syarat diterimanya hadits. Juga Imam Muslim yang dalam mukadimah Shahihnya telah menilai buruk terhadap para periwayat hadits dhaif dan munkar, juga terhadap orang yang meninggalkan khabar yang shahih. Ini juga kecenderungan pendapat Imam Abu Bakar bin Al ‘Arabi pemimpin madzhab Malikiyah dizamannya, juga Imam Abu Syamah pemimpin madzhab Syafi’iyah pada zamannya, dan pendapat Imam Ibnu Hazm, dan selainnya.
Kedua: Jika telah ada dalam hadits shahih dan hasan yang memuat makna dan maksud pelajaran dan peringatan, maka tidak ada artinya bergantung dengan hadits lemah lagi lembek. Allah Ta’ala telah mencukupkan dengan baik dibanding yang jelek, dan jarang sekali makna agama, akhlak, dan taujih, yang tidak ditemukan dalam hadits shahih dan hasan, betapa itu sudah memadai. Tetapi lemahnya keinginan, dan mengambil segala apa saja yang datang kepadanya tanpa mengkaji dan muraja’ah, membuat begitu mudahnya tersebarnya hadits dhaif secara mutlak.
Ketiga: Sesungguhnya hadits dhaif tidak boleh disandarkan kepad Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan bentuk kata jazm (pemastian). Disebutkan dalam kitab At Taqrib dan Syarhnya: “Jika anda hendak meriwayatkan hadits dhaif tanpa isnad, maka jangan katakan: Qaala Rasulullah kadza (Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda begini).’ Atau kata lainnya yang semisal pemastian. Tetapi katakanlah: ruwiya ‘anhu kadza (diriwayatkan darinya begini), atau disampaikan kepada kami darinya begini, atau telah sampai, atau telah dating, atau telah dinukil darinya, dan yang semisalnya dari bentk kata tamridh (bentuk kata yang menunjukan adanya cacat), seperti rawaa ba’dhuhum (sebagian mereka meriwayatkan). Maka, apa yang menjadi kebiasaan sebagian khatib, juru nasihat, ketika menyampaikan hadits dhaif dengan ucapan: Qaala Rasulullah (Rasulullah telah bersabda), adalah pekara yang tidak dapat diterima.
Keempat: Ulama yang membolehkan menggunakan hadits dhaif dalam urusan targhib dan tarhib tidaklah membuka pintu bagi semua yang dhaif. Mereka memberikan syarat untuk itu, yakni ada tiga syarat:
- Kedhaifannya tidak terlalu.
- Hadits tersebut masih masuk ke dalam prinsip dasar syariat yang dapat diamalkan melalui Al Quran dan Sunah yang shahih.
- Ketika mengamalkannya tidak memastikan dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, justru hendaknya berhati-hati.
Dari sini telah jelas, bahwa tak satu pun ulama membolehkan menggunakan hadits dhaif dengan pembolehan tanpa ikatan dan syarat. Bahkan mereka memberikan tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan.
Sebagai tambahan dari syarat asasi ini, yaitu hendaknya hal itu pada fadhailul a’mal saja tidak berakibat pada hukum syariat. Dalam pandangan saya, hendaknya syarat ini ditambah dua syarat lagi, yakni:
- Isinya tidak mengandung hal-hal yang bombastis dan ditolak oleh akal, syariat, dan bahasa. Para imam hadits telah menyebutkan bahwa hadits palsu dapat diketahui melalui qarinah (petunjuk) pada perawinya dan apa yang diriwayatkannya.
- Tidak bertentangan dengan nash syar’i lain yang lebih kuat darinya.
Wallahu A’lam