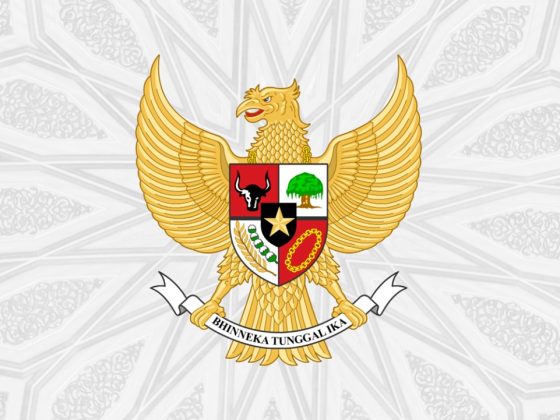Oleh: Taufik M. Yusuf Njong
Pada Tahun 70-an silam, diskusi tentang keharusan bermazhab/tidak bermazhab sempat ‘memanas’ ketika Syeikh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi mengarang kitab Allamazhabiyah Akhthar Bid’ah Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah untuk membantah kelompok yang tidak bermazhab, mengajak berijtihad dan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah yang diserukan oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin Albani cs. Syeikh Albani dan kawan-kawan kemudian mengarang kitab Bid’ah Ta’asshub Al-Mazhabi untuk membantah tulisan Syeikh Al-Buthi rahimahumullah.
Diantara diskusi yang tercatat antara Syeikh Al-Buthi dan Syeikh Albani adalah terkait perkataan Syeikh Albani bahwa mazhab-mazhab para imam (mujtahid) tidak mutlak benar seluruhnya, karena bisa saja ada kesalahan dalam ijtihad mereka. Syeikh Al-Buthi kemudian menimpali bahwa ijtihad para imam tersebut (tetap) dianggap sebagai AGAMA terlepas apakah ijtihad tersebut benar atau salah, dengan alasan (diantaranya) adanya pahala atas ijtihad mereka (baik ijtihad tersebut benar ataupun salah). Disini, Syeikh Albani kemudian ngotot mengatakan bahwa ijtihad para ulama jika salah bukanlah termasuk AGAMA.[1]
Syeikh Albani dan kawan-kawan dalam kitabnya Bid’ah Ta’asshub Al-Mazhabi kemudian mengklaim bahwa Syeikh Al-Buthi di penghujung diskusi ruju’ dari pendapatnya dan mengakui bahwa ijtihad seorang ulama jika telah jelas kesalahannya maka itu tidak termasuk AGAMA.[2]
Agama (tsawabitnya), syari’at dan wahyu merupakan hal-hal prinsipil yang diakui dan disepakati kebenarannya oleh semua umat Islam. Dan oleh para ulama kontemporer, kata-kata tersebut sering ditampilkan sebagai lawan dari kata-kata fiqih, turats atau al-fikr al-Islamy. Dalam bahasa lain, agama, syariat dan wahyu adalah perkara-perkara tetap yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah (al-ma’lum minaddin biddharurah). Sebaliknya, fiqih, turats dan pemikiran Islam adalah hasil dari ijtihad/eksplorasi akal para ulama Islam yang tidak ma’shum dari sumber-sumbernya seperti Al-Qur’an dan Sunnah.
Perbedaan pendapat dan perbedaan kecenderungan para ulama dalam memahami istilah-istilah seperti agama, syariat, fiqih, turats, dan lain-lain merupakan salah satu sebab meruncingnya perdebatan antara kelompok ulama yang cenderung kepada ijtihad dan tajdid di satu sisi serta mereka yang dengan rendah hati ‘istiqomah’ dengan pendapat para aimmah salaf disisi lain. Perbedaan tersebut juga menjadi salah satu penghambat dan penolakan sebagian ahli ilmu terhadap tajdid (Kontemporer) sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikhul Azhar Dr. Ahmad Thayyib. Beliau mengatakan bahwa upaya tajdid modern terhalang oleh dua sebab:
- Tidak (mampu/mau) membedakan antara yang tsabit/tetap dalam agama dan yang mutaghayyirat/berubah-ubah.
Islam sebagai sebuah agama mencakup beberapa prinsip yang tidak berubah-ubah. Prinsip tersebut cocok untuk setiap zaman dan tempat dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman ataupun perkembangan tekhnologi.[3]
- Tidak (mampu/mau) membedakan antara syari’at dan fiqih (turats), menggolongkan ke dalam syariat pendapat dan pemahaman manusia (ulama) serta menempatkan pendapat dan pemahaman manusiawi tersebut pada derajat nash ma’shum (teks-teks yang terjaga dari kesalahan). (Sejatinya), Syari’at harus dibedakan dengan jelas dari fiqih. Syari’at adalah teks-teks yang jelas dari Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun istinbath/eksplorasi para ulama dari para ahli fiqih, para ulama ushul, para ulama tafsir, para ulama hadis dan para ulama ahli kalam seharusnya hanya dipandang sebagai pengetahuan manusiawi atau turats (warisan/khazanah klasik) yang bisa diambil dan ditinggalkan.[4]
Dari pemaparan Syeikhul Azhar diatas, penting digarisbawahi bahwa turats atau fiqih atau terkadang disebut dengan al-fikr al-Islamy (pemikiran/eksplorasi/ijtihad para ulama Islam) bukanlah suatu hal yang ma’shum dan sakral. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam karya beliau Kaifa Nata’amalu Ma’a At-Turats wa At-tamazhub wa Al-Ikhtilaf ketika mensyarah prinsip keenam dari 20 prinsip yang dipopulerkan As-Syahid Hasan Al-Banna bahwa “Setiap orang boleh diambil atau ditolak pendapatnya, kecuali Al-Ma’shum (Rasulullah) saw. Setiap yang datang dari kalangan salaf dan sesuai dengan Kitab dan Sunah, kita menerimanya. Jika tidak sesuai dengannya, maka Kitabullah dan Sunnah RasulNya lebih utama untuk diikuti. Namun demikian, kita tidak boleh melontarkan kepada orang-orang -oleh sebab sesuatu yang diperselisihkan dengannya- kata-kata caci maki dan celaan. Kita serahkan saja kepada niat mereka, dan mereka telah berlalu dengan amal-amalnya.”
Setelah menjelaskan empat kelompok besar yang mewariskan turats kepada kita yaitu kelompok fuqaha, kelompok muhadditsin, kelompok mutakallimin dan kelompok shufi, Syeikh Al-Qaradhawi berkata: “Jika turats atau warisan klasik kita berasal dari hasil eksplorasi para ulama Islam dan ia tidak memiliki sifat ‘ishmah dan kesakralan, maka adalah hak kita untuk menyikapinya dengan kritis dan teliti. Dan juga menganggapnya sebagai suatu kekayaan besar yang harus dimanfaatkan, dengan cara memilih dan menyaring dari khazanahnya, mana yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan nash agama serta dibutuhkan untuk kemaslahatan umat Islam. Sambil meninggalkan hal-hal yang tidak tepat atau sudah tidak relevan lagi untuk diaplikasikan dizaman kita sekarang ini.” [5]
Bersikap kritis terhadap turats bukan berarti bahwa “kita membusungkan dada di hadapan turats fiqih kita, atau merendahkan derajat para fuqaha kita, atau berupaya menggantikannya dengan unsur-unsur asing lain yang berlawanan dengan tabiatnya, bukan. Perlu dibedakan antara hal tersebut dengan memandang kepada fiqih dengan pandangan ‘ishmah. (Sebab), Tidak semua turats bisa diterima dan tidak semuanya juga harus ditolak. Atau dengan ungkapan lain, turats tidak semuanya mampu menghadapi tantangan atau menjawab problematika kontemporer dan tidak semuanya juga gagal untuk berinteraksi dengan kemodernan…” [6]
Namun, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh mereka yang berinteraksi dan mengkritisi turats para ulama kita yang agung menurut Syeikh Al-Qaradhawi:
Pertama, meneliti mata rantai periwayatannya, sehingga kita mengetahui sahih atau tidaknya nash tersebut. Karena tidak semua yang dinisbatkan kepada kalangan salaf adalah benar dan secara fakta bahwa hal itu berasal dari mereka.
Kedua, menyadari hak kita untuk mengkritisinya, selama hal tersebut tidak ma’shum (dan bukan masail al-qat’iyah).
Ketiga, wajib berlaku adil dan bersikap moderat dalam melakukan penilaian dan kritik terhadap turats tersebut.
Keempat, tidak melampaui batas dalam mengkritisinya, sehingga menjadi celaan dan cemoohan.[7]
Kemudian.., ada dua kelompok manusia yang menjadi musuh tajdid kontemporer sebagaimana disebutkan oleh Syeikhul Azhar Dr. Ahmad Thayyib:
Pertama, mereka yang mendaku sebagai kelompok yang membawa pencerahan/tanwir. Mereka ini menyerang turats kaum muslimin (dengan membabi buta) dan melakukan distorsi terhadap turats tanpa memiki keahlian untuk mengetahui dan memahaminya (tidak ilmu dan juga wawasan) serta tidak punya adab dan rasa hormat terhadap turast yang diagungkan oleh lebih dari 1,5 miliyar umat Islam.[8]
Lebih jauh, mereka menyerang Al-Azhar dan mengkambinghitamkan manhaj Al-Azhar atas setiap tindakan terorisme. Mereka yang mengkampanyekan tajdid al-khitab ad-dini ini sebenarnya menganggap Al-Azhar sebagai problem dan ingin menjadikannya hanya sebagai museum.
Barangkali, kritik keras dari Al-Imam Al-Akbar Dr. Ahmad Thayyib terhadap Presiden Universitas Kairo Dr. Mohamed Osman Elkhosht dalam Al-Azhar International Conference on Renovation of Islamic Thought pada Januari 2020 lalu agar tidak menyerang turats bisa menjelaskan kelompok pertama yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Akbar. Yaitu? Kelompok liberal yang minim ilmu-ilmu perangkat ijtihad namun getol menyerukan tajdid.
Disamping mereka, ada kelompok kedua yang tidak memahami tajdid al-khitab ad-dini melainkan kembali kepada pendapat-pendapat salaful ummah dan salihul mukminin di tiga abad yang pertama. Mereka ini ingin ‘membekukan’ risalah Al-Azhar, ilmunya dan dakwahnya sebatas beribadah dengan sebuah mazhab tertentu, keyakinan tertentu serta bentuk-bentuk dan ‘tradisi-tradisi’ yang mereka anggap sebagai AGAMA yang seolah-olah tidak ada AGAMA selainnya.[9]
Kembali ke laptop. Pada intinya, turats atau al-fikr al-islamy adalah hasil eksplorasi para ulama Islam di bidang mereka masing-masing berdasarkan pemahaman dan dugaan kuat mereka terhadap nash. Karenanya, hasil pemikiran/pemahaman mereka ini seberapa pun ia disarikan dari Al-Qur’an dan Sunnah tetaplah (sebuah pemahaman) produk akal manusia yang tidak ma’shum dan mungkin untuk dikritisi. Turats atau pemikiran Islam bukanlah wahyu, ia bukan Islam atau syariat sehingga jika ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita, kita tidak bisa langsung memvonisnya telah melawan Islam/agama atau menentang syariat. Perlu ditarik garis batas yang jelas antara Islam/syariat dengan pemahaman para imam (terlebih lagi para ulama-ulama pengikut mereka yang datang kemudian) terhadap sumber-sumber tasyri’ tersebut.
Ya, benar bahwa ucapan bahwa ijtihad para ulama tidak sakral dan bisa dikritisi memang terkesan terlalu vulgar di zaman kita dimana penguasaan terhadap bahasa Arab, hadis dan ilmu-ilmu lain yang menjadi syarat ijtihad semakin berkurang. Adalah wajar jika kemudian banyak orang menentang ijtihad atau tajdid kontemporer. Akan tetapi, para ulama yang berijtihad dan melakukan tajdid tersebut sejatinya tidak pernah mengobrak-abrik apa yang merupakan hal-hal prinsipil dalam Islam (al-ma’lum min ad-din biddharurah) atau perkara-perkara yang menjadi konsensus para ulama (bukan sekedar klaim ijma’).
Sampai disini, jika kita sepakat bahwa turats bukanlah wahyu yang sakral, maka tajdid kontemporer sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan bahkan wajib. Atau setidaknya, kita (harus) mampu berbaik sangka dan memberikan uzur kepada mereka yang memang kapabel dalam keilmuannya untuk melakukan tajdid kontemporer demi kemudahan dan kemaslahatan umat Islam sendiri.
Sebagai contoh, jika kita membuka hasil-hasil Muktamar NU lima puluh tahun lalu. Disana akan dijumpai sebuat fatwa yang mengharamkan pemakaian dasi dan celana panjang (pantalon). Pendapat semacam ini jelas sangat kasuistik dan sifatnya sangat spesifik. Diperlukan wacana baru untuk menyikapi dan memandangnya secara kontekstual.[10]
Merupakan hal yang kurang tepat memaksakan pendapat haramnya dasi dan celana panjang (yang dulu pernah difatwakan era penjajahan dan setelahnya) di era kontemporer. Sebab pendapat tersebut bukanlah wahyu yang pasti benar, tapi hanya sebuah ijtihad para ulama yang bisa benar dan salah dan mungkin cocok untuk zaman mereka, bukan di zaman kita.
Dalam bukunya Kaifa Nata’amalu Ma’a At-Turats wa At-tamazhub wa Al-Ikhtilaf, Syeikh Al-Qaradhawi menjelaskan beberapa contoh kritik para ulama terhadap turats, baik itu terkait dengan tafsir, fiqih, ilmu kalam dan tasawuf yang terlalu panjang untuk dikutip disini. Disamping ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentang tajdid dan ijtihad yang hangat untuk didiskusikan. Dan semoga kita bisa mendiskusikannya di kesempatan lain.
Wallahu A’lam bisshawab.
Catatan Kaki:
[1] Allamazhabiyah Akhtharu Bid’ah Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah, Syeikh Muhammadiyah Sa’id Ramadhan Al-Buthi, hal 61, cet Dar Al-Farabi tahun 2005.
[2] Bid’ah Ta’asshub Al-Mazhabi, Muhammad ‘Id Abbasi, hal 345 cet Al-Maktabah Al-Islamiyah, Amman-Yordania.
[3] Al-Qaul At-Thayyib, Dharurah At-Tajdid, Syeikhul Azhar Dr. Ahmad Thayyib hal: 174 juz 1, Cet. Dar Al Hokama Publishing, 2021.
[4] Ibid, hal: 178.
[5] Kaifa Nata’amalu Ma’a At-Turats wa At-tamazhub wa Al-Ikhtilaf, Dr. Yusuf Al-qaradawi hal: 45 file pdf dari website Syeikh (atau lihat buku terjemahannya ‘Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf, hal 54 cet: Akbar Media.
[6] Al- Qaul At-Thayyib, hal: 178 juz 1.
[7] Kaifa Nata’amalu Ma’a At-Turats wa At-tamazhub wa Al-Ikhtilaf, hal: 45 file pdf.
[8] Al- Qaul At-Thayyib, hal: 142 juz 1.
[9] Ibid, hal 188.
[10] Tasawuf sebagai Kritik Sosial, Dr. K.H. Said Aqil Siroj, hal 58, penerbit Mizan, cet 1 September 2006.