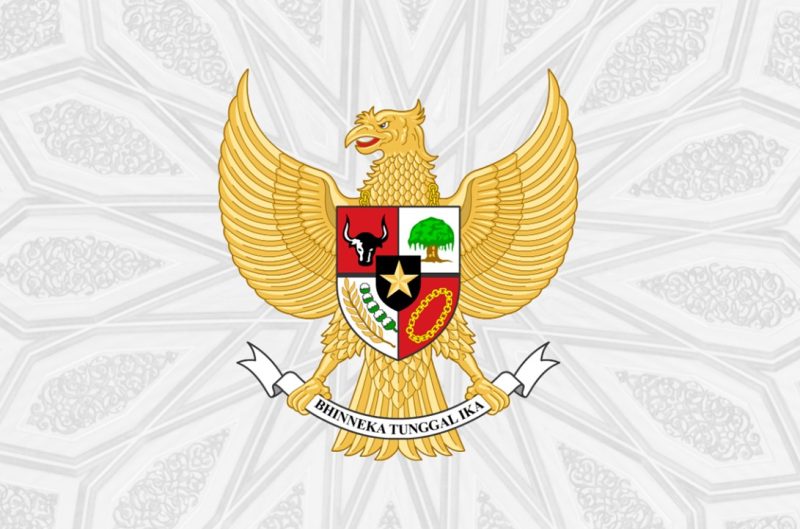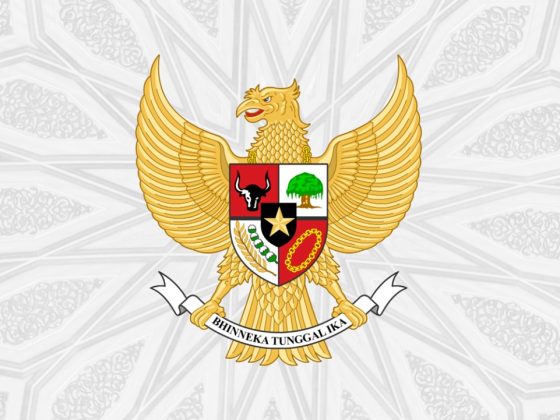Oleh: Akmal Sjafril
Setiap bulan Juni, bangsa Indonesia mengenang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (RI). Meski demikian, dalam sejarah RI, sebenarnya ada beberapa titik kontroversial penting yang berkaitan dengan sejarah kelahiran Pancasila.
Salah satu masalah yang selalu mengemuka dari masa ke masa adalah tentang relasi antara Islam dan Pancasila. Di titik ekstrem yang satu, ada sebagian kalangan dari umat Muslim yang menganggap bahwa Pancasila adalah thaghut atau berhala, dan menerimanya sebagai dasar negara adalah sebuah kemusyrikan. Di titik ekstrem lainnya ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Pancasila berada pada posisi yang superior dibandingkan semua agama, dan karenanya, Islam di Indonesia pun harus tunduk pada Pancasila. Pihak yang kedua ini berhaluan sekuler-liberal. Di antara kedua kelompok tersebut, ada golongan yang tidak mempertentangkan antara Islam dan Pancasila.
Haruskah Dipertentangkan?
Pertanyaan pertama yang perlu dijawab dalam mendudukkan posisi Islam dan Pancasila adalah: apakah keduanya mesti dipertentangkan? Baik untuk jawaban “ya” atau “tidak”, kita memerlukan dasar pemikiran yang kuat.
Pada kenyataannya, gerakan Islam di Indonesia kerap kali ditekan dengan menggunakan Pancasila sebagai dalihnya. Para aktivis dakwah dan pergerakan Islam biasa disebut sebagai ‘Islamis’, sementara pada posisi berseberangan ada golongan ‘nasionalis’ atau ‘Pancasilais’.
Buya Hamka, sebagai ulama-penulis yang sangat produktif, banyak mengekspresikan keprihatinannya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketika Pancasila selalu dijadikan alasan untuk mengebiri hak-hak umat Muslim. Simaklah, misalnya, kejengkelan beliau yang diekspresikan dengan penuh amarah (padahal Hamka dikenal lembut dalam bertutur kata) dalam artikelnya yang berjudul “Pancasilais Munafik”:
“Bertahun-tahun lamanya dasar negara Pancasila itu dipermainkan di ujung bibir dan telah dimuntahkan dari hati. Menjadi isi dari pidato untuk orang banyak, tetapi dilanggar dalam tindakan hidup sehari-hari, dipandang khianat orang lain yang dituduh tidak setia kepada Pancasila, dan orang yang tidak berdaya itu tidak diberi kesempatan membuktikan bahwa si penuduh itulah sebenarnya yang menjadikan Pancasila itu hanya permainan bibir.”
Dalam artikelnya, Buya Hamka tengah mengkritik keras Orde Lama, yang waktu itu baru saja diruntuhkan dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan diturunkannya Soekarno dari tampuk kekuasaan. Ketika itu, dua orang tokoh Orde Lama, yaitu Soebandrio dan Yusuf Muda Dalam, tengah menjalani persidangan dan menghadapi tuntutan hukuman mati. Hamka sendiri adalah tokoh yang secara langsung mengecap pahitnya kezaliman Orde Lama. Sebagai seorang sastrawan Muslim, beliau merasakan langsung diskriminasi dan permusuhan yang begitu keras dilancarkan oleh Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra). Sebagai tokoh ulama, beliau bahkan sempat mendekam di balik jeruji penjara selama dua tahun dan mengikuti serangkaian interogasi yang panjang tanpa persidangan sama sekali; semua karena tuduhan makar yang tidak ada buktinya sama sekali.
Pada masa Orde Baru, ironisnya, Buya Hamka kembali menjadi ‘tokoh utama’ dalam pergerakan Islam yang merasakan langsung kezaliman rejim yang berkuasa. Jika di awal masa pemerintahannya Soeharto nampak begitu akomodatif dengan aspirasi umat Muslim – salah satunya dengan mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara langsung meminta Hamka untuk menjadi ketua pertamanya – namun keadaan berubah begitu cepat dengan munculnya seruan di instansi-instansi pemerintah untuk menggelar perayaan Natal dan Idul Fitri secara berbarengan. MUI merespon tegas dengan mengeluarkan fatwa haramnya perayaan Natal bersama. Akibat fatwa tersebut, Buya Hamka ditekan habis-habisan dan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dan menarik fatwa tersebut dari peredaran. Hanya saja, menurut Hamka, dengan ditariknya fatwa itu dari peredaran, tidak berarti fatwanya tidak berlaku lagi. Setelah pengunduran dirinya, Hamka malah menegaskan pendapat pribadinya bahwa fatwa itu sebenarnya masih sangat ringan. Sebab, mengikuti perayaan Natal bersama hukumnya bukan hanya haram, tapi juga menyebabkan pelakunya menjadi murtad. Demikianlah pendapat Buya Hamka.
Dengan melihat sejarah yang demikian, memang tidak mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Islam dan Pancasila bisa hidup berdampingan. Akan tetapi, sementara Islam adalah ajaran yang diyakini komprehensif dan dapat dipastikan kemurnian ajarannya, nampaknya Pancasila justru ‘pasrah’ di tangan para penafsirnya. Orde Lama dan Orde Baru sama-sama menggunakan Pancasila untuk menekan pergerakan Islam, namun keduanya memaknai Pancasila dengan cara yang berbeda.
Memaknai Pancasila
Debat mengenai dasar negara dalam Sidang Konstituante pada tahun 1957 cukup menarik untuk disimak. Dalam sidang tersebut, Masyumi kembali mengajak bangsa Indonesia untuk mempertimbangkan Islam – dan bukan Pancasila – sebagai dasar negara.
Penolakan Masyumi terhadap Pancasila sebagai dasar negara telah dikemukakan dengan sangat baik oleh Moh. Natsir. Dalam orasinya, Natsir menjelaskan bahwa Pancasila tidaklah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, sebab jauh sebelum Pancasila itu lahir, agama telah mewarnai isi hati sanubari bangsa. Pada kesempatan itu Natsir menegaskan:
“Pancasila sebagai filsafat negara itu bagi kami adalah kabur dan tak bisa berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah mempunyai dan memiliki satu ideologi yang tegas, terang dan lengkap dan hidup dalam rakyat Indonesia sebagai tuntutan hidup dan sumber kekuatan lahir dan bathin, yakni Islam.
Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampa, vakum, tak berhawa.”
Kata-kata di atas diungkapkan oleh Natsir setelah menggambarkan kontrasnya Pancasila dengan kondisi negara pada saat itu, di mana Pancasila tidak memiliki sikap yang tegas pada aliran komunisme yang anti-Tuhan, meskipun sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila hendak dijadikan ‘netral’, sehingga akomodatif terhadap agama dan komunisme sekaligus, padahal yang demikian itu tidaklah mungkin, dan kenyataannya memang tidak pernah terwujud.
Meski demikian, Natsir tidak serta-merta menolak Pancasila. Sebab, dalam lanjutan orasinya, beliau menyatakan pula:
“Tak ada satu pun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara.
Dalam Islam terdapat kaidah-kaidah yang pasti, di mana pure concepts dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak.”
Dengan kata lain, Natsir hendak mengatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang kosong belaka, yang bahkan tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri. Makna Pancasila dapat dipermainkan oleh siapa saja, sebab ia memang tidak memiliki kelengkapan konseptual yang mapan. Tidak seperti Islam yang memiliki pandangan yang jelas soal ketuhanan, misalnya, Pancasila justru dapat dimanfaatkan untuk ideologi anti-Tuhan sebagaimana terjadi dalam masa Orde Lama dahulu.
Dalam beberapa karya tulisnya, Buya Hamka pernah menggarisbawahi masalah pemaknaan ini. Beliau mengingatkan bahwasanya Soekarno pernah mengatakan bahwa jika Pancasila itu ‘diperas’, maka akhirnya dia menjadi satu prinsip saja, yakni ‘gotong royong’. Hamka sendiri menentang pendapat yang demikian. Sebagai balasannya, beliau mengemukakan opini bahwa Pancasila tidak perlu ‘diperas’, namun jika dicari urat tunggangnya, maka ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itulah yang akan ditemukan. Hal ini, menurut Buya Hamka, sejalan dengan logika berpikir umat Muslim yang memahami segala sesuatunya dengan mengembalikannya pada sumbernya, yaitu konsep ketuhanan.
Naquib al-Attas, cendekiawan Muslim asal Malaysia, menyatakan hal yang sama ketika membicarakan the Worldview of Islam (pandangan-alam Islami), meskipun ia tidak sedang membicarakan Pancasila. Bagi seorang Muslim, segala konsep yang dikenal dalam hidupnya (konsep agama, kenabian, wahyu, manusia dan kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya) bersumber dari konsep ketuhanan. Oleh karena itu, konsep kemanusiaan dalam pandangan orang sekuler atau ateis sangat berbeda dengan konsep kemanusiaan dalam pandangan seorang Muslim yang taat dengan agamanya.
Maka tidaklah mengherankan jika Soekarno merasa mampu ‘memeras’ Pancasila menjadi ‘gotong royong’, sedangkan Hamka tidak menggunakan istilah yang sama (yaitu “memeras”) namun memahami sila pertama sebagai ‘akar tunggang’ dari Pancasila itu sendiri. Semuanya bersumber dari worldview yang dijadikan pegangan oleh masing-masing. Fenomena ini menguatkan pendapat Natsir di atas, yaitu bahwa Pancasila tidak bisa memberikan penjelasan konseptual secara komprehensif, melainkan justru dapat ditafsirkan dengan cara yang berlawanan, tergantung siapa penafsirnya.
Pancasila dalam Pandangan Islam
Para pemimpin Masyumi yang berdebat alot dalam Sidang Konstituante 1957 tidaklah menyatakan Pancasila sebagai thaghut (kecuali jika memang ada yang memposisikannya demikian), tidak pula memberi saran untuk menghapuskannya. Pancasila adalah kesepakatan antar elemen bangsa. Meski demikian, Pancasila tidaklah mampu menjelaskan kandungan maknanya sendiri, sebab ia hanya terdiri atas lima sila yang begitu singkat.
Islam, sebaliknya, adalah seperangkat konsep dan tata nilai yang komprehensif. Tidak seperti Pancasila yang sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja, Islam tidak dapat dimaknai semaunya. Meskipun ada ruang untuk perbedaan pendapat, namun dalam hal-hal yang prinsip tidak ada perdebatan. Oleh karena itu, Islam memiliki kemampuan untuk menafsirkan Pancasila, dan tidak sebaliknya. Itulah yang dimaksud oleh Natsir ketika mengatakan bahwa Pancasila justru akan mendapatkan ruh penggerak dari Islam. Dengan cara itu, Pancasila akan benar-benar memiliki kekuatan konsep yang dapat dijabarkan dengan baik dalam tataran praktis.
Dalam sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, terdapat konsep tauhid yang dapat dengan mudah dipahami oleh umat Muslim. Menurut Buya Hamka, umat Muslim-lah yang paling siap untuk menerima sila pertama ini, dan mereka tak mungkin menentangnya. Segala-galanya didasari oleh keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan negeri ini pun sebagian besarnya berasal dari kontribusi para mujahid yang berjuang atas seruan agama; para ulama menyuruh mereka berjuang mengusir penjajah, semangat jihad dikobarkan, dan yang mereka teriakkan dalam perjuangan itu tidak lain adalah pekik takbir. Bangsa Indonesia sadar sepenuhnya bahwa negeri ini berdaulat karena rahmat Allah SWT, dan karenanya, mereka tak bisa dipaksa-paksa untuk mengabaikan Tuhannya.
Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, sangatlah problematis. Bagi para penganut Hak Asasi Manusia (HAM) ala Barat, homoseksualitas, aborsi tanpa syarat, berzina, mengkonsumsi minuman keras, euthanasia, semuanya adalah hak asasi manusia yang tak boleh dilarang-larang. Akan tetapi bagi seorang Muslim, hak-hak manusia adalah sepanjang yang dibolehkan oleh agama. Demikian juga bagi rakyat Indonesia yang meyakini bahwa Sila kedua ini hanya dapat dipahami dengan merujuk pada ‘akar tunggangnya’, yaitu Sila pertama. Maka, kemanusiaan yang benar adalah kemanusiaan yang berketuhanan, bukan yang mengabaikan Tuhan. Kata “adil” dan “adab” pun sangat multitafsir. Bagi kaum feminis, pembagian harta warisan yang setara itulah yang adil. Bagi George W. Bush, invasi ke Irak dan Afghanistan tidak lain untuk mengajari rakyat kedua negeri itu untuk beradab. Islam pun memiliki konsep tersendiri soal keadilan dan adab, bahkan kedua istilah ini terambil dari kosa kata Islam dalam bahasa Arab.
Selanjutnya, sila-sila yang lain pun dapat dimaknai dengan baik jika menggunakan ‘kacamata Islam’. Islam telah memiliki konsep yang jelas tentang persatuan dan nasionalisme, sehingga terhindar dari fanatisme kebangsaan yang sempit. Islam juga mengajarkan caranya bermusyawarah yang baik, juga menjelaskan hal-hal yang boleh dimusyawarahkan dan hal-hal yang harus dirujuk pada aturan agama; dengan kata lain, musyawarah yang berketuhanan. Tentu saja, Islam pun dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadilan sosial.
Permasalahan konseptual yang dimiliki oleh Pancasila bisa menjadi bara dalam sekam, sehingga sejarah sangat mungkin berulang. Dari waktu ke waktu, ada saja yang berusaha mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Ada yang membela Lady Gaga dengan alasan Indonesia bukan negara agama, padahal tidak sedikit yang menolak artis yang sama dengan berpegang teguh pada Pancasila, yang justru mengakui otoritas agama sebagai sumber nilai dalam kehidupan bernegara.
Tentunya, kita tidak mengharapkan bangsa Indonesia terus larut dalam perdebatan ini. Seharusnya semua orang bisa menjadi Muslim yang baik sekaligus Pancasilais yang baik. Sudah semestinya Pancasila tidak mengambil posisi berseberangan dengan Islam yang menjadi agama mayoritas di negeri ini. Dengan Islam, Pancasila tidaklah mati, melainkan justru semakin hidup.