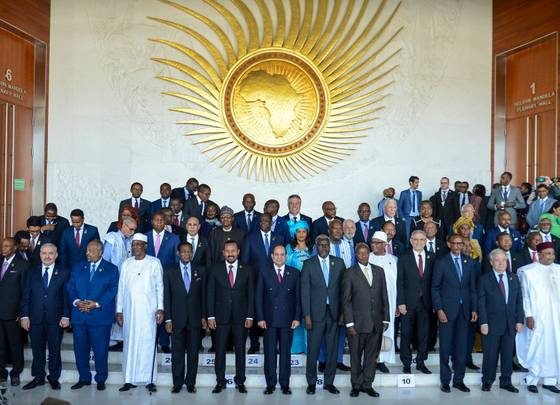Oleh: Taufik M. Yusuf Njong
Taqlid dan Bermazhab, Antara Ekstrim dan Permisif
Banyak penulis sejarah fiqih islamy mengatakan bahwa abad kedua dan ketiga hijriah adalah masa keemasan fiqih islamy. Di periode ini, ilmu fiqih tumbuh dan berkembang pesat lantaran beberapa sebab diantaranya ‘lahirnya’ para mujtahid mumpuni yang berani mengeksplorasi hukum-hukum fiqih dari sumber-sumber tasyri’. Kapasitas dan keberanian mereka juga disupport oleh stabilitas politik dinasti Abbasiyah yang saat itu memang berada puncak kejayaannya, serta telah dikodifikasikannya sunnah yang memudahkan para mujtahidin untuk mengetahui shahih atau dha’ifnya sebuah hadis.
Masa keemasan fiqih islamy ini kira-kita berlangsung sampai pertengahan abad keempat hijriah hingga kemudian fiqih menjadi stagnan dan masuk ke periode taqlid dimana para fuqaha lebih ‘nyaman’ untuk menjadi pengikut salah satu mazhab fiqih yang ada dan telah dikodifikasikan. ‘Ketidakpedean’ para fuqaha untuk berijtihad di periode ini kemudian diperparah dengan semakin melemahnya dinasti Abbasiyah yang kemudian hancur di tangan pasukan Mongol di awal abad ketujuh hijriah. Tampilnya sejumlah mujtahid gadungan dengan fatwa-fatwa mereka yang nyeleneh kemudian memantapkan para fuqoha untuk ‘menutup’ pintu ijtihad. Mereka khawatir akan rusaknya ‘agama’ karena ulah para pendaku ijtihad yang miskin perangkat ilmu tersebut.
Di periode taqlid ini, trend meringkas disiplin ilmu (fiqih dan lainnya) dalam bentuk matan, lalu dikomentari dalam bentuk syarah dan kemudian diulas lagi dalam bentuk hasyiah/al-hawasyi berkembang dan menjadi familiar diantara para fuqoha. Meskipun sumbangsih ini dianggap sedikit jauh dari semangat ijtihad, namun beberapa usaha para ulama yang tampil mentarjih pendapat-pendapat dalam mazhab serta merapikan kembali fiqih satu mazhab layak diapresiasi sebagai sumbangsih besar untuk fiqih Islam.[1]
Terlepas dari trend tersebut, anjuran untuk berijtihad tetap digaungkan oleh sebagian kecil fuqoha seperti Ibnu Taimiyah cs dan para fuqoha hanabilah secara umum yang menolak klaim tertutupnya pintu ijtihad. Semangat ini kemudian digaungkan oleh Imam As-Suyuthi di abad ke 9 H dan kemudian oleh Imam As-Syaukani di abad ke 13 H meskipun mendapatkan penentangan dari banyak ulama.
Konsekuensi dari klaim tertutupnya pintu ijtihad adalah diwajibkannya taqlid kepada salah satu mazhab yang empat. Di Indonesia, pendapat Sayyid Al-Bakry (pengarang kitab I’anah At-Thalibin yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia) bahwa seorang muqallid (tanpa merinci apakah muqallid tersebut awam atau ahli ilmu) WAJIB mengikuti salah satu mazhab yang empat adalah salah satu pendapat yang paling populer yang dijadikan acuan tidak bolehnya memfatwakan pendapat di luar salah satu mazhab yang empat.[2] Syeikh As-Showi al-Maliki bahkan memfatwakan lebih jauh, bahwa orang yang keluar dari mazhab yang empat adalah sesat menyesatkan.[3]
Hal penting lain yang tidak bisa dikesampingkan di balik sikap para ulama yang mewajibkan taklid adalah adanya fatwa keras Ibnu Hazm yang tidak membolehkan siapapun untuk taqlid kepada siapapun baik kepada orang (ulama) yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dalam Al-Muhalla-nya, Ibnu Hazm bahkan mewajibkan setiap orang (seberapapun bodohnya ia) untuk ‘berijtihad’ semampunya.[4] Pendapat Ibnu Hazm yang mengecam taklid dan mewajibkan ijtihad ini kemudian diikuti oleh Imam As-Syaukani di abad ke 13 H dengan ungkapan yang tak ‘sevulgar’ ungkapan Ibnu Hazm. Imam As-Syaukani menjelaskan bahwa maksud semua orang harus ‘berijtihad’ bukanlah agar semua orang harus berusaha sampai pada derajat ijtihad/mujtahid. Akan tetapi yang dituntut oleh Imam As-Syaukani adalah agar mereka menanjak ke derajat yang sedikit lebih tinggi dari taklid dengan cara menanyakan hukum syar’i suatu masalah kepada para ulama serta menanyakan kepada mereka landasan hukum tersebut dari Qur’an atau Sunnah dan kemudian ia beramal berdasarkan ‘riwayat’ tersebut.[5]
Dari penjelasan Imam As-Syaukani diatas, sejatinya ‘ijtihad’ yang ‘diwajibkan’ oleh Ibnu Hazm terhadap orang awam sebenarnya lebih dekat kepada makna lughawi ketimbang makna ‘ijtihad para mujtahid’ secara epistemologi yang banyak disebutkan dan dipahami dalam disiplin ilmu Ushul fiqh. Karenanya, argumen untuk membantah Ibnu Hazm dkk bahwa mengajak semua orang (termasuk awam) untuk berijtihad akan menimbulkan kekacauan sebenarnya tak relevan. Sebab maksud Ibnu Hazm mengajak semua orang untuk ‘berijtihad’ bukanlah agar semua orang awam dari petani, tukang kayu, pedagang dan lain-lain untuk sampai pada derajat ijtihad dan melakukan istinbath dari Al-Qur’an dan Sunnah, bukan!
Sebagai salah seorang ulama yang paling getol menyerukan ijtihad dan menolak dengan keras mereka yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup sejak abad ke 4 H, Imam As-Suyuthi mungkin paling inshof ketika mengatakan bahwa taklid semestinya tidak ‘dipaksakan’ kepada setiap orang di setiap masa. Sebab, ‘memaksakan’ taklid kepada setiap orang di setiap masa bisa berarti pengguguran terhadap kewajiban ijtihad yang merupakan fardhu kifayah yang harus ada di setiap masa dan tak boleh ‘dinonaktifkan’. Berbeda dengan Ibnu Hazm, Imam As-Suyuthi juga tidak ‘mewajibkan’ semua orang untuk berijtihad, beliau justru mengklaim adanya konsensus para ulama bahwa orang awam boleh bertaklid.[6]
Menariknya, Imam As-Suyuthi termasuk yang cenderung pada pendapat bahwa ada tingkatan pertengahan (ittiba’) antara tingkatan taqlid dan ijtihad, padahal mayoritas para ulama Ushul fiqih hanya membagi dua tingkatan saja yaitu muqallid dan mujtahid. Dalam risalahnya Ar-Radd ‘Ala Man Akhlada Ila Al-Ardh Wa Jahala Anna Al-Ijtidad Fi Kulli Ashr Fardh Imam As-Suyuthi mengutip perkataan Imam Ibnu Abdil Barr bahwa, “Taqlid menurut sebagian ulama berbeda dengan Ittiba’, karena Ittiba’ adalah engkau mengikuti pendapat seseorang berdasarkan apa (argumen) yang ‘nampak’ bagimu dari ‘kejelasan’ perkataannya dan kebenaran mazhabnya (pendapatnya). Sedangkan taqlid adalah engkau mengikuti pendapat seseorang padahal engkau tidak tau ‘sudut pandang’ (argumen) pendapat (tersebut) dan maknanya..” [7] Kemudian Imam As-Suyuthi juga mengutip pendapat Ibnu Khuwaizi Mandad al-Maliki untuk membedakan antara taqlid dan Ittiba’.[8]
Mafhum mukhalafah definisi taqlid menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa-nya dan Imam Al-Haramain dalam Al-Waraqat-nya (bahwa Taqlid adalah menerima pendapat seseorang tanpa hujjah) sebenarnya mengesankan bahwa menerima/mengikuti pendapat seseorang berdasarkan hujjah bukanlah taqlid. Dan Imam Ghazali juga menganggap bahwa orang awam yang mengikuti/ittiba’ mufti (mujtahid) tidak dianggap sedang bertaqlid. Sebab, ia menerima pendapat seseorang (mufti) berdasarkan hujjah yaitu hujjah ijma’ wajibnya awam bertanya kepada mufti. Dan tingkatan orang awam yang menerima pendapat mufti mujtahid juga tidak bisa dianggap bahwa dia ada di tingkatan ijtihad. Dari sini pendapat sebagian ulama bahwa ada tingkatan ittiba’ antara tingkatan taqlid dan ijtihad sebenarnya adalah sebuah penfapat/ijtihad yang berpotensi benar. Wallahu A’lam.
Kembali ke laptop..!
Di pertengahan abad ke 20, pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam As-Syaukani yang mencela taqlid kemudian di serukan kembali oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin Albani meskipun tak sekeras Ibnu Hazm dan Imam As-Syaukani. Namun, oleh lawan-lawannya, Albani tetap dianggap sebagai penerus Ibnu Hazm dan dicap sebagai neo-zahiriyah. Sikap Syeikh Albani dkk yang mencela taklid dan bermazhab (fanatisme bermazhab) ditentang oleh Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari (wakil masyaikhah terakhir dinasti Ottoman) dengan makalahnya, Allamazhabiyah Qantarah Alladiniyah, lalu oleh Syeikh Muhammad Al-Hamid Al-Hamawi dalam kutaibnya, Luzum Ittiba’ Mazahib Al-Aimmah Hasman Lilfaudha Ad-Diniyah, dan yang paling terkenal adalah bantahan Syeikh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi dalam karya beliau, Allamazhabiyah Akhtharu Bid’ah Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah.
Syeikh Al-‘Allamah Al-Mujahid Muhammad Al-Hamid atau Syeikh Al-Hamawi sebagaiman dikenal oleh Ikhwan Mesir adalah salah seorang ulama Al-Azhar asal Suriah yang sangat dekat dengan Hasan Al-Banna. Beliau, Syeikh Mustafa As-Siba’i dan Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah diantara para ulama Al-Azhar yang pertamakali mengembangkan harakah islamiyyah di Suriah. Syeikh Al-Buthi pernah menulis sebuah makalah berjudul Hama Wa ‘Alimuha Ar-Rahil untuk mengenang Syeikh Al-Hamid. Dan oleh murid Syeikh Albani, Syeikh Mahmud Mahdi Al-Instanbuli, Syeikh Al-Hamid ‘dituduh’ telah menempuh jalannya para majusi karena sikapnya yang ngotot mengajak bermazhab.[9]
Jika demikian, lalu apa hukum taqlid dan bermazhab yang paling dekat dengan kebenaran? Tentunya harus dirinci.
- Orang awam yang sama sekali tidak mempelajari disiplin-disiplin ilmu agama dan bahasa Arab dengan berjenjang maka boleh baginya (bahkan wajib) untuk ‘bertaqlid’. Dan ini sebenarnya adalah juga pendapat sebagian dari ulama yang mencela taqlid seperti Imam As-Suyuthi dan Imam Ibnu Abdil Barr hingga Syeikh Albani.[10]
- Golongan ahli ilmu yang belum sampai tingkatan ijtihad maka tetap dibolehkan baginya taqlid dan yang lebih utama adalah melakukan Ittiba’ dan berusaha memahami dalil. Imam As-Syatibi merinci dan membagi golongan ahli ilmu ini dalam dua golongan lagi yang panjang untuk dijelaskan dan terlalu rentan diperdebatkan. Pendapat ini juga pendapat As-Syahid Hasan Al-Banna dalam prinsip yang ke 7 dari Ushul ‘Isyrin
- Mujtahid, maka haram baginya taqlid. Masuk dalam kategori ini juga Mujtahid Fil Mazhab jika hasil Ijtihadnya justeru berbeda dengan ijtihad Imam mazhabnya maka haram baginya mentarjih pendapat Imam mazhabnya atas hasil Ijtihadnya.[11]
Terakhir, Kita bisa menilai bahwa pendapat Ibnu Hazm dan Imam As-Syaukani yang mewajibkan ijtihad (dengan mafhum ijtihad menurut mereka) kepada semua orang bahkan orang awam sekalipun adalah pendapat yang terlalu keras dan tidak relevan dengan kondisi mayoritas umat Islam. Terlebih lagi kaum muslimin non Arab yang buta dengan bahasa Arab, mewajibkan mereka untuk menanyakan dalil yang tidak mereka pahami dan tidak tau bagaimana memahami dalil adalah ijtihad mereka yang bisa jadi adalah sebuah ijtihad yang salah.
Wallahu A’lam.
[1] Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Mazaahib Al-Fiqhiyah, Dr. Ali Gomaa, hal 440 dst (dengan sedikit perubahan) Cet Dar Alsalam tahun 2012.
[2] I’anah At-Thalibin, Sayyid Al-Bakri, hal 17, Juz 1, Cet Dar Ihya Kutub Al-Arabiya.
[3] Hasyiah As-Showi ‘Ala Tafsir Al-Jalalain, hal 9, juz 3, Cet Dar Al-Jail, Beirut.
[4] Al-Muhalla Bi Al-Atsar, Ibnu Hazm Al-Andalusy, hal 85, jilid 1, Cet ke 3 Dar Al-kotob Al-Ilmiyah Beirut-Lebanon, tahun 2002.
[5] Al-Qaul Al-Mufid Fi Adillah Ijtihad Wa At-Taqlid, Muhammad Bin Ali As-Syaukani, hal 15, Cet Mathba’ah Al-Ma’ahid, Mesir.
[6] Ar-Radd ‘Ala Man Akhlada Ila Al-Ardh Wa Jahala Anna Al-Ijtidad Fi Kulli Ashr Fardh, Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuthi, hal 3, Cet Maktabah As-Tsaqafah Ad-Diniyah, Kairo.
[7] Ibid, hal 44.
[8] Ibid, hal 46
[9] Allamazhabiyah, Syeikh Al-Buthi, hal 153.
[10] Arrad Ala Man Akhlada… hal 3 dan 47 dan kitab Bid’ah Ta’asshub Al-Mazhabi, hal 14.
[11] Allamazhabiyah, Syeikh Al-Buthi, hal 49.